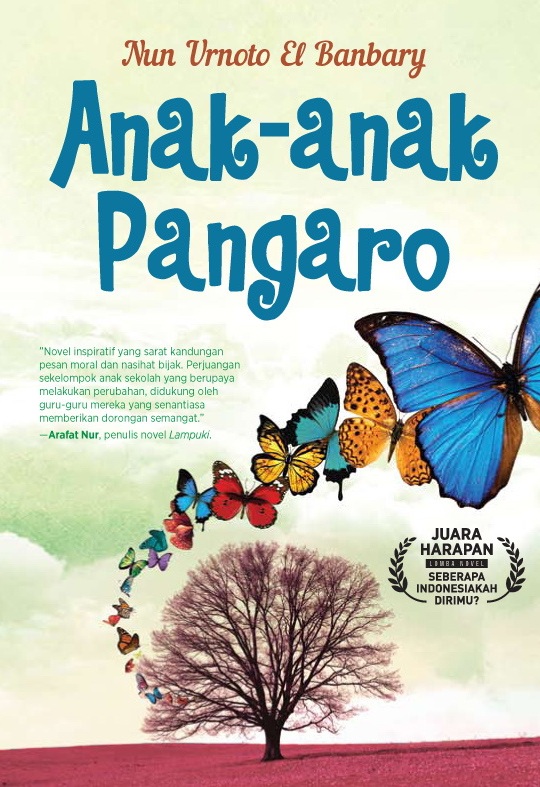Oleh: Abrari Alzael
Budayawan, tinggal di Madura
Banyak cara bagi orang-orang yang narsis. Ada yang tidak sekolah namun ingin memiliki ijazah. Ada pula yang merasa bangga dipanggil doktor dari yang sebenarnya tidak kuliah. Orang-orang menjadi gila hormat dengan cara-cara yang jauh dari terpandang. Karena itu ia ingin ada penampakan di depan atau di belakang namanya, gelar akademik.
Pada pihak lain, ada juga orang-orang yang di depan atau di belakang namanya tidak perlu diberi embel-embel. Ini soal pilihan dan pertanggungjawaban akademik. Pilihan ini lahir dari situasi substantif karena doktor atau bukan doktor bukan dilihat dari aspek bertebarnya gelar. Melainkan ia dipandang dari aspek kompetensi, basis keilmuan yang dimiliki. Jika ragu-ragu dengan kedoktorannya, untuk apa menyandangkan plakat itu di dekat namanya?
Tetapi jangan lupa, negeri ini terlalu kreatif untuk urusan yang tidak diharapkan. Doktor, mungkin terlalu mudah untuk dipalsukan oleh siapa saja yang ingin melakukannya. Dalam kasus beras, bangsa ini geger karena ada SDM yang berhasil menjadikan sintetis seolah-olah organik. Tetapi benar kata iklan, kebohongan seringkali terendus ketika bersanding dengan kebenaran. Pendek kata, apa yang tidak bisa dilakukan untuk tujuan kepentingan indiviual dan komunal-terbatas di republik ini?
Kasus Frans, anggota DPR RI yang dilaporkan mantan staf ahlinya, Denty, karena anggota dewan yang terhormat itu diduga melabelkan doktor di depan namanya. Padahal, ia belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang doktor dari sisi akademik dan administratif. Jika dugaan ini benar, tentu ini hanya sebagian yang terendus dari sebagian besar praktik pensitetisan gelar di republik ini.
Jika dugaan ini tidak terbukti, tentu karena ada motif politik dari pelapor terhadap terlapor menjelang pemilukada yang ditengara akan melibatkan Frans. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menegaskan dan mengorek kebenaran supaya negeri ini memiliki kepastian hukum. Pembiaran atas ketidakpastian kebenaran ini akan menjadi boomerang dan paradoks dimana anutan konstitusi mendedahkan persamaan di depan hukum. Terkecuali, hukum hendak dimutilasi untuk membela kepentingan. Bila ini yang diinginkan, tentu saja, pelajaran hukum yang dimengerti rakyat, belum sampai pada fatsun ini.
Riwayat gelar sintetis ini bermula dari pendataan yang tidak jelas dan menjauh dari sisi akurasi-akademik. Ini tidak saja pada ranah strata dalam pendidikan. Dalam politik di Indonesia, kejadian yang lebih horor terjadi. Begitu banyak orang yang mati berpartisipasi aktif dalam pemilu, pilpres, maupun pemilukada. Begitu juga, tak terhitung jumlah anak-anak yang belum cukup syarat menjadi pemilih pemula, namanya lolos menjadi pemilih. Ini artinya, rekrutmen pemilih, data, dan dan pengangkatan pantarlih muncul sebegitu mudah. Logika sederhananya, sesuatu yang mudah di dapat, akan begitu mudah pula untuk lenyap.
Mencuatnya gelar sintetis saat ini bukan kali yang pertama. Jauh sebelum kasus yang diduga melilit anggota parlemen ini juga terjadi pada guru yang mendapat tunjangan sertifikasi yang pada akhirnya terbukti menggunakan ijazah sarjana bodong. Ini jelas lebih monster karena pendidik menjadikan kebohongan sebagai alat untuk mendidik. OLeh karena itu, peserta didik yang berdekatan dengan pembohong, pada akhirnya berpotensi untuk meniru sebagian kebohongan yang dipertontokan pendidiknya saat pembelajaran. Kecuali, kebohongan negeri ini sengaja diciptakan untuk mewujudkan kebenaran yang dilacurkan, serupa organik yang disintetiskan atau serumpun ijazah yang dimakzulkan. [*]